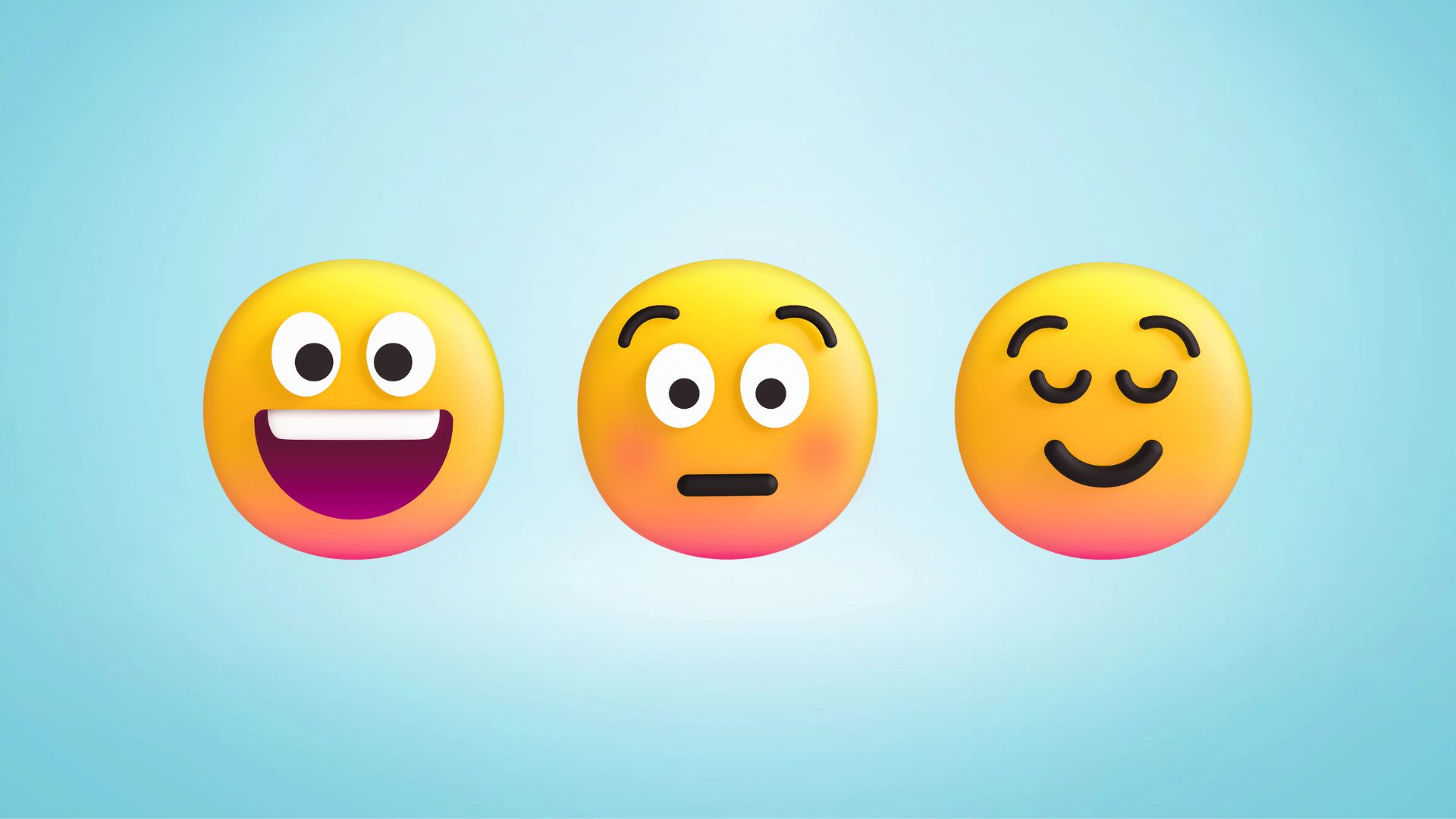“Fajar Sadboy lagi, Fajar Sadboy lagi,” gumam saya sembari menyisir varian informasi arus utama yang menyertakan Fajar Sadboy di dalamnya. Sadboy dan Sadgirl adalah istilah populer di budaya media sosial kita guna menamai orang-orang yang mudah sedih. Apakah ini glorifikasi kesedihan dalam jiwa anak muda yang kategori umurnya kerap dicap labil? Mungkinkah sekaligus ajang refleksi umat manusia yang kadar kelelahan mentalnya sudah berkutat di stadium tiga dan empat? Atau hanya viralitas semu yang menjadi kendaraan media untuk mencari penonton dadakan? Entahlah.
Mencari ujung kesedihan bin kegalauan sama halnya seperti ungkapan lirik lagu almarhum Glen Fredly Sedih Tak Berujung. Tapi ngomong-ngomong, apakah kita sudah benar-benar bahagia? Atau jangan-jangan manusia berlabel Sadboy dan Sadgirl adalah kita?
Bicara bahagia, saya tidak ingin membahasnya dari sisi golongan rentang usia; gen X,Y,Z, baby boomer atau alpha. Sudah terlalu banyak perdebatan lahir di media sosial perkara saling menyalahkan antar kelompok usia ini. Bagaimana kalau kita melihatnya dari data global saja? Walaupun bahagia adalah sebuah perasaan yang sifatnya subjektif, temporer dan terjadi karena multifaktor, bahagia ternyata rutin diukur oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sejak 2013 melalui riset berjudul World Happiness Report. PBB pun menetapkan tanggal 20 Maret adalah Hari Bahagia Sedunia (International Happiness Day). Riset ini dilakukan terhadap kurang lebih 150 negara dan memiliki 6 indikator pengukuran negara bahagia; pendapatan domestik per kapita, dukungan sosial, harapan hidup sehat, kebebasan menentukan pilihan hidup, kedermawanan dan persepsi terhadap korupsi. Posisi 1 penduduk terbahagia sedunia sampai saat ini masih teguh tersemat ke negara Finlandia sebagai jawara bahagia tak tergoyahkan selama 5 tahun berturut-turut.
Di mana posisi Indonesia? Tampaknya kita, warga sipil Indonesia, harus cukup berbesar hati dengan posisi ke 87 dari 146 negara. Lumayan. Setidaknya tidak berada di kumpulan 10 besar terakhir. Menilik angkanya, kondisi bahagia Indonesia masuk ke kategori angka ‘menengah ke bawah’, hampir serupa dengan dominasi kelas sosial ekonomi masyarakat Indonesia yang kerap disebut masyarakat kelas menengah alias middle class society.
Aspiring Middle Class
Bank Dunia (World Bank) melalui laporannya yang berjudul Aspiring Indonesia-Expanding The Middle Class (2019) memaparkan 5 jenis kelas sosial di Indonesia; miskin (poor), rentan (vulnerable), menuju kelas menengah (aspiring middle class), kelas menengah (middle class) dan kelas atas (upper class). Ternyata, porsi paling besar itu bukan didominasi oleh middle class (20% populasi) yang hanya sejumlah 53,6 juta penduduk melainkan oleh aspiring middle class (44% populasi) atau sejumlah 114, 7 juta penduduk. Kelompok aspiring middle class ini umumnya berada di wilayah perkotaan dengan jumlah tertinggi berada di ibukota Jakarta. Capaian pendidikan umumnya lulusan SMP dan SMA dan dominasi terbesar pekerjaan adalah karyawan upah rendah dan usaha pribadi.
Marilah kita fokus pada kategori terbesar ini yakni mereka yang angka konsumsi bulanannya berkisar antara Rp 532.000 sampai dengan Rp 1.200.000 per orang per bulan. Sementara, berdasarkan informasi pendapatan rata-rata orang Indonesia yang dilansir dari Kumparan (2019) menyatakan angkanya adalah Rp 4,6 juta/bulan. Artinya, kelompok terbesar ini taraf hidupnya masih jauh sekali di bawah rata-rata nasional. Maka tak heran jika masyarakat Indonesia masih mudah dan marak dijajah pinjaman online (pinjol).
Pendapatan rendah dan kemampuan kognitif masyarakat yang juga rendah adalah paket sempurna untuk menjadi korban pinjol. Korban pinjol yang bertumbangan secara sukarela, suka sengaja atau suka abai tak jadi soal. Namun faktanya, OJK mencatat aduan terhadap fintech peer-to-peer (P2P) lending resmi maupun pinjol ilegal mencapai 19.711 kasus selama kurun waktu 2019-2021. Adapun tiga alasan tertinggi para korban pinjol menurut riset No Limit Indonesia (2021) antara lain untuk membayar hutang, karena berasal dari golongan menengah ke bawah yang butuh uang dan karena dana cair lebih cepat. Sementara, dari sisi demografi, 42% korban jeratan pinjol adalah mereka yang berstatus guru, 21% korban PHK dan 18% ibu rumah tangga.
Jika kemampuan pemenuhan kebutuhan hidup yang pokok saja masih kembang kempis, kalang kabut dan gali lubang tutup lubang, bagaimana bisa dikatakan hidup sejahtera? Apalagi bahagia? Pendapatan per orang jelas memiliki efek domino dalam siklus hidup. Pertama, efek instan dari pendapatan rendah adalah daya beli rendah. Jika daya beli rendah, maka pasokan produksi barang dan jasa akan mengalami penurunan permintaan dimana imbasnya ke lapangan kerja yang menyusut sehingga rentan terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK). Kedua, ketiadaan pekerjaan dan pendapatan adalah pemantik meluasnya kemiskinan. Ketiga, ancaman meningkatnya kriminalitas. Polri melaporkan kejahatan terjadi sebanyak 276.507 kasus di 2022. Angka kriminalitas ini naik 7,3% dibandingkan tahun 2021.
Bicara pendapatan per orang sejatinya baru bicara turunan dari satu indikator negara bahagia sebagaimana yang dirumuskan PBB. Apa kabar 5 indikator yang lain? Misalnya persepsi terhadap korupsi. Data dari Indonesian Corruption Watch (ICW) per Juni 2022 menunjukkan bahwa potensi kerugian negara akibat kasus korupsi mengalami peningkatan. Tercatat ada 1.387 kasus korupsi di tingkat penyidikan namun aparat penegak hukum baru bisa merealisasikan 18 persen dari keseluruhan kasus tersebut. Tak tanggung-tanggung, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga berhasil menyeret 34 kepala daerah, hakim agung sampai seorang rektor universitas negeri ke pengadilan tipikor sepanjang 2022.
Menulis ini pun membuat saya ingin menenggak parasetamol karena mengernyitkan kening tak sudah-sudah. Betapa situasi negeri ternyata turut mempengaruhi pikiran para warga sipil seperti saya.
Cara Pindah Kuadran
Pekerjaan rumah kita pada dasarnya bukan hanya perkara menaikkan ranking negara bahagia dari peringkat 87 menuju 50 besar. Namun, bagaimana agar kelompok aspiring middle class yang sejumlah 114,7 juta penduduk tadi benar-benar bisa berpindah kuadran ke middle class? Melihat kenyataannya, titel aspiring middle class ini bak garnis dalam piring hidangan yang membuat kelompok ‘menuju kelas menengah’ ini terlihat menyerupai dan akan segera mencapai ‘kelas menengah’ yang ideal karena dilabeli kemampuan finansial yang aman. Nyatanya, tidak sesederhana itu.
Masalah seputar ekonomi dan pendidikan dari perspektif makro nan majemuk ini memang tidak bisa diselesaikan sendirian oleh pemerintah. Namun, kebijakan pemerintah yang tepat sasar terkait kesejahteraan guru, dosen, pegawai dan buruh di Indonesia juga bisa menjadi batu pijakan menuju Indonesia Emas 2045. Pendidikan dulu, sekarang dan nanti akan tetap menjadi tulang punggung suatu negara yang maju, berdaya dan berkarakter. Saya jadi ingat kata dokter Ryu Hasan, “Pendidikan yang tinggi memang tidak menjamin seseorang itu akan kaya raya, tapi setidaknya akan ‘memperbesar peluang’ seseorang untuk menjadi kaya.”
Lifting aspiring Indonesians into the middle class means having more of them finishing high school & ideally going further”, demikian bunyi salah satu simpulan dari laporan Bank Dunia ini terhadap kelompok aspiring middle class. Membacanya seolah dejavu dengan petuah bijak populer orang tua dari jaman dulu, ”Nak, kamu sekolah yang rajin dan setinggi mungkin yah.”
Sebagai individu yang sudah mengenyam pendidikan formal di berbagai institusi, saya pun merasa ‘bahagia’ juga tidak serta merta linier dengan tingginya pendidikan. Rating bahagia bergantung pada banyak angka variabel dalam rumus kehidupan seseorang. Kita tidak bisa menjaga angkanya harus terus naik dan meroket, karena menjaganya tetap seimbang saja sudah sebuah prestasi. Seiring bertambah umur, maka kemampuan saya mengatur stres, sedih, kecewa dan setumpuk emosi negatif itu juga makin mahir. Makin mahir pula dalam kemampuan terlihat bahagia di situasi yang sebenarnya tidak bahagia-bahagia amat. Kesimpulan subjektif saya; bahagia itu sesungguhnya relatif dan situasional. Satu lagi, bisa kita kontrol juga kok, asal tahu caranya.
Sebuah tagar populer di media sosial yang telah dipakai lebih dari 3,7 juta kiriman sepertinya cocok untuk kita yang kadang juga menjadi Sadboy dan Sadgirl saat mengalami kegamangan temporer. #janganlupabahagia yah!
Oleh : Sari Bayurini Samudra, S.Sn., M.M.
Dosen Ilmu Komunikasi UIN Raden Fatah Palembang
–End–