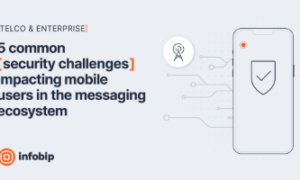Karena kopi Sumsel sejatinya bukan pemain baru, ia bukan remaja tanggung yang baru belajar diseduh, ia sudah tua, matang, dan aromanya pun tak kalah semerbak dari kopi-kopi legenda dunia.
Tapi entah kenapa, aromanya justru lebih dihargai di luar pagar daripada di beranda rumah sendiri. Ini seperti punya anak cantik, pintar, jago masak, tapi tiap malam minggu malah duduk sendiri di teras, tak pernah diajak kencan. Sementara tetangga sebelah yang anaknya baru bisa nyeduh teh manis, sudah dilamar investor dari Swiss.
Fakta bahwa produktivitas kopi kita masih 892 kg/Ha bukan cuma angka kering, tapi alarm bahwa ada yang salah dalam sistem. Ibarat petani memegang emas, tapi ditutup lumpur, lalu disuruh jual ke pasar dengan harga arang, bukan salah petani, tapi salah sistem yang belum ramah terhadap mereka. Minimnya akses pembiayaan membuat mereka stuck di zaman giling manual, padahal dunia sudah bicara soal blockchain coffee trading dan traceable QR code dari kebun ke cangkir.
Lebih dari itu, kopi bukan sekadar komoditas. Ia adalah identitas, budaya, dan ekonomi kreatif yang bisa menyerap tenaga kerja, meningkatkan ekspor, hingga mengharumkan nama daerah.
Di Toraja, kopi jadi maskot turisme. Di Gayo, kopi jadi diplomasi. Di Vietnam, kopi jadi penyumbang devisa. Di Ethiopia, kopi jadi kebanggaan nasional. Nah, di Sumsel? Kopi kadang hanya jadi bingkisan dinas saat kunjungan kerja.
Sudah waktunya kita berhenti sekadar meratapi aroma kopi yang hanya mampir di FGD. Mari beralih dari “Forum Gaya Duduk” ke “Forum Gerak dan Dorong”.
Bangun ekosistem
Pemerintah daerah, lembaga keuangan, pelaku usaha, hingga komunitas anak muda harus membangun ekosistem yang membuat kopi Sumsel bukan hanya tumbuh, tapi naik kelas, dari lereng ke rak-rak supermarket dunia, dari kebun ke kedai hipster di Berlin dan Brisbane.
Dukung koperasi, dorong inovasi, perkuat branding, dan yang terpenting jadikan petani sebagai mitra, bukan pelengkap penderita. Jangan biarkan petani kita terus minum kopi sachet murah sambil memandangi biji kopi mahal yang justru dibeli murah oleh tengkulak ekspor.
Karena kalau kita tak bergerak sekarang, bisa jadi suatu hari nanti anak cucu kita ngopi di kafe luar negeri, dan ketika ditanya “Ini kopi dari mana?”, mereka akan menjawab “Entahlah, enak sih… katanya dari Sumatera Selatan. Tapi di rumah sendiri nggak pernah nemu beginian”. Saat itu terjadi, sesungguhnya yang pahit bukan kopinya, tapi nasib kita.
Oleh karena itu, patut direnungkan karena Sumsel bukan kekurangan kopi, tapi kekurangan panggung buat si kopi tampil jadi bintang. Sudah terlalu lama kopi kita hanya jadi figuran dalam film dokumenter pertanian, padahal layak jadi pemeran utama dalam iklan internasional dengan tagline “Strong, bold, and proudly grown in South Sumatera”.
Sudah saatnya kita berhenti jadi daerah penghasil kopi yang hanya dikenal di kalangan sempit, lalu berani tampil di peta dunia. Jangan sampai slogan kita berubah jadi, Kopi Sumsel, banyak di kebun, minim di kemasan”. Itu miris, bos, seperti punya suara emas tapi malah disuruh jaga parkiran di depan panggung karaoke.
Pemerintah, OJK, Bank Indonesia, BPS, dinas-dinas, dan para pengusaha, bisa duduk tidak hanya untuk diskusi, tapi juga untuk menyeduh strategi. Jangan biarkan biji kopi kita kehilangan cita rasa hanya karena terlalu lama dibiarkan menunggu di gudang keputusan.
Perlu juga dukungan pemuda kreatif Sumsel, bangkitlah, bikin konten kopi, buka kedai, jual ke luar negeri. Kopi kita terlalu berharga untuk hanya diseduh di belakang rumah.
Karena, hei… kalau bukan kita yang bangga dan ngopi pakai kopi sendiri, ya jangan salahkan Starbucks kalau mereka terus jualan kopi Sumsel dengan label negara lain.
Pastikan di masa depan nanti, aroma kopi Sumatera Selatan bukan cuma tercium di lereng, tapi juga semerbak di kota, harum di dunia, kalau ada yang tanya, “Kopi terenak dari mana, Bos?” Kita bisa jawab dengan bangga “Dari tanah kami [Sumatera Selatan], diseduh dengan cinta, dijual dengan cerita. Mantap!!.[***]