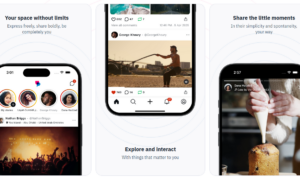Sumselterkini.co.id, – FENOMENA kepala daerah yang aktif di media sosial telah menjadi tren yang semakin menonjol dalam lanskap politik Indonesia. Aktivitas mereka di platform digital telah menciptakan dinamika baru dalam hubungan antara pemimpin dan masyarakat. Fenomena ini memiliki dimensi yang kompleks dan perlu dilihat secara komprehensif.
Transformasi Ruang Publik Politik
Media sosial telah mentransformasi cara pemimpin berkomunikasi dengan publik. Dalam perspektif ilmu politik, hal ini dapat dilihat sebagai bentuk evolusi dari konsep “ruang publik” . Ruang publik digital ini memungkinkan interaksi langsung antara pemimpin dan masyarakat, potensial mendemokratisasi komunikasi politik. Namun, pertanyaan kritisnya adalah: apakah interaksi ini substantif atau hanya bersifat performatif?
Dualisme Performativitas dan Substansi
Kepala daerah yang aktif di media sosial sering terjebak dalam “politik performatif” – situasi di mana tindakan politik lebih diarahkan untuk konsumsi visual daripada penyelesaian masalah. mereka berada dalam “panggung depan” (front stage) yang terus-menerus, di mana citra dan kesan menjadi lebih penting daripada substansi.
Di sisi lain, kepala daerah yang bekerja dalam diam mungkin fokus pada “politik substantif” – penyelesaian masalah nyata masyarakat. Namun, dalam era di mana visibilitas menjadi ukuran legitimasi, mereka berisiko kehilangan dukungan publik karena kurangnya eksposur.
Populisme Digital dan Alienasi Politik
Fenomena ini berkaitan erat dengan munculnya “populisme digital” – strategi politik yang memanfaatkan media sosial untuk membangun hubungan langsung dengan masyarakat sambil mengabaikan institusi perantara.
Dalam konteks Indonesia, populisme digital seringkali ditandai dengan kebijakan yang mengedepankan solusi cepat, terlihat, dan menghibur.
Paradoksnya, meskipun publik merasa lebih “dekat” dengan pemimpin, mereka mungkin justru semakin teralienasi dari proses pembuatan kebijakan yang sesungguhnya. Konten yang menghibur di media sosial dapat mengalihkan perhatian dari diskusi substantif tentang kebijakan publik.
Distorsi Agenda Kebijakan
Dalam perspektif teori agenda-setting, media sosial dapat mendistorsi prioritas kebijakan. Kepala daerah mungkin cenderung memprioritaskan kebijakan yang “terlihat baik” di media sosial daripada kebijakan yang benar-benar dibutuhkan masyarakat. Ini menciptakan bias sistemik terhadap kebijakan yang bersifat jangka pendek, visual, dan mudah dikomunikasikan.
Masalah struktural yang kompleks—seperti ketimpangan ekonomi, reformasi birokrasi, atau perencanaan infrastruktur jangka panjang—mungkin terabaikan karena tidak memberikan konten yang menarik untuk media sosial.
Tantangan bagi Literasi Politik
Fenomena ini menimbulkan tantangan serius bagi literasi politik warga. Publik perlu mengembangkan kemampuan untuk membedakan antara kebijakan substantif dan kebijakan performatif. Literasi politik di era digital tidak hanya berarti memahami sistem politik, tetapi juga kemampuan kritis untuk melihat melampaui kemasan visual kebijakan.
Dalam perspektif demokrasi deliberatif, diskusi publik seharusnya berfokus pada argumentasi dan pertukaran ide tentang kebaikan bersama, bukan pada personalitas atau citra pemimpin. Media sosial cenderung mendorong ke arah yang sebaliknya.
Menuju Keseimbangan Baru
Tantangan bagi pemimpin dan masyarakat adalah menemukan keseimbangan baru. Kepala daerah perlu memanfaatkan media sosial untuk transparansi dan akuntabilitas, sambil tetap memprioritaskan kebijakan substansial. Di sisi lain, masyarakat perlu mengembangkan kewaspadaan kritis terhadap konten politik di media sosial.
Pendekatan yang ideal adalah integrasi antara komunikasi politik yang efektif dan kebijakan yang substansial. Kepala daerah dapat menggunakan media sosial tidak hanya untuk menampilkan aktivitas, tetapi juga untuk melibatkan masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan yang sebenarnya.
Catatan Akhir
Fenomena kepala daerah yang aktif di media sosial mencerminkan transformasi yang lebih luas dalam komunikasi politik di era digital. Meskipun menawarkan potensi untuk transparansi dan keterlibatan yang lebih besar, fenomena ini juga membawa risiko penyederhanaan masalah publik dan pengalihan dari isu-isu substantif.
Masyarakat perlu mengembangkan literasi politik yang kritis untuk tidak terjebak dalam pesona visual media sosial. Mereka harus mampu mengevaluasi kebijakan berdasarkan dampaknya terhadap masalah nyata, bukan berdasarkan seberapa baik kebijakan tersebut dipresentasikan di media sosial.
Pada akhirnya, kualitas demokrasi akan ditentukan oleh kemampuan kolektif kita untuk melampaui politik performatif dan mengembangkan diskusi publik yang substantif tentang masa depan bersama. Media sosial bisa menjadi sarana untuk memperkuat demokrasi, tetapi hanya jika digunakan secara bijaksana oleh pemimpin dan masyarakat.[***]
Oleh :
Yulion Zalpa ( Peneliti Politik Pusat Riset Sosial Politik, Ekonomi dan Kemasyarakatan /PROSPEK) & Dosen FISIP UIN Raden Fatah Palembang